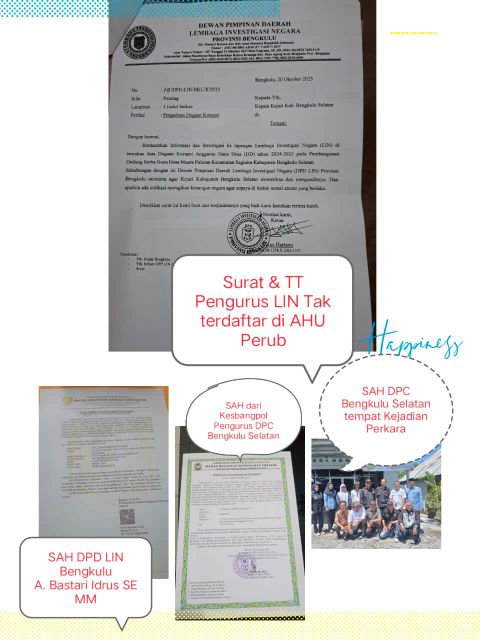Patrolihukum.net // Sorong, Papua Barat Daya – Proses mediasi perkara perdata di Pengadilan Negeri (PN) Sorong menuai kritik tajam lantaran dinilai tidak transparan dan terkesan memaksakan kehendak salah satu pihak. Mediasi yang mempertemukan PT. Bagus Jaya Abadi (BJA) selaku penggugat dengan Hamonangan Sitorus selaku tergugat, kini menjadi sorotan publik, terutama karena dinilai menerapkan pola yang mirip praktik “beli kucing dalam karung”.
Praktik ini, menurut pengamat hukum dan etika, Wilson Lalengke, mengingatkan pada pola pemilu era Orde Baru. Saat itu, rakyat dipaksa memilih lambang partai tanpa tahu siapa calon legislatif yang sebenarnya mereka pilih. Kini, pola serupa diduga diterapkan dalam ruang sidang mediasi di PN Sorong, namun dalam bentuk “bayar kucing dalam karung”.

Dalam mediasi yang digelar belum lama ini, kuasa hukum PT. BJA datang dengan proposal yang cukup mengejutkan. Mereka menawarkan penyelesaian dengan cara “membagi dua” lahan yang menjadi obyek sengketa, ditambah pembayaran kompensasi senilai Rp2,5 miliar. Anehnya, pihak penggugat tidak menyertakan satu pun dokumen legalitas atas kepemilikan lahan yang diklaimnya.
Saat tergugat, Hamonangan Sitorus, mempertanyakan bukti kepemilikan dan letak lahan yang dimaksud, kuasa hukum PT. BJA, Albert Frasstio, enggan menjelaskan. Alasannya, hal tersebut merupakan materi pokok perkara yang hanya bisa dibuka di sidang pokok, bukan saat mediasi.
Namun yang menjadi kejanggalan, sikap hakim mediator, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., justru dinilai condong berpihak kepada penggugat. Hakim terlihat mendukung penuh ide masuk ke sidang pokok perkara tanpa memberi ruang cukup bagi tergugat untuk memahami secara utuh duduk perkara, khususnya menyangkut lokasi dan legalitas lahan yang disengketakan.
“Ini seperti disuruh bayar kucing dalam karung. Kita tidak tahu isi karungnya apa, kucingnya jenis apa, warnanya apa, bahkan mungkin bukan kucing,” ungkap Hamonangan dengan nada kecewa.
Dalam dokumen proposal yang dibawa kuasa hukum PT. BJA, tergambar bahwa lokasi lahan yang dimaksud berada di area yang masuk dalam zona perairan laut. Fakta ini menimbulkan kebingungan besar, karena wilayah laut tentu tidak bisa dimiliki secara pribadi dan tidak memiliki dasar hukum untuk diklaim sebagai lahan pribadi.
“Kalau lahan yang diklaim saja masih gelap, bagaimana mungkin kita bisa melanjutkan ke tahap ganti rugi atau pembagian?” tegas Hamonangan.
Ia menegaskan bahwa dirinya hadir dalam mediasi dengan itikad baik untuk menyelesaikan sengketa secara damai, namun dengan catatan bahwa semua pihak transparan dan jujur soal data dan fakta.
Menurut Lalengke, seorang mediator, baik hakim maupun non-hakim, semestinya menjadi fasilitator netral yang memahami secara rinci pokok sengketa. Seorang hakim mediator wajib memberi ruang kepada kedua pihak untuk menyampaikan keberatan, argumentasi, dan harapan masing-masing secara terbuka.
“Jika pihak yang dimediasi tidak mengetahui apa isi ‘karung’ yang dipersengketakan, maka mediasi hanya akan jadi formalitas. Mediasi seperti itu tidak beradab dan jauh dari prinsip keadilan,” tegasnya.
Keberhasilan proses mediasi, kata dia, sangat tergantung pada kualitas kepemimpinan mediator. Jika mediasi gagal karena ketidaksiapan mediator menavigasi kepentingan para pihak, maka itu merupakan catatan buruk dalam kinerja pengadilan.
Di akhir analisanya, Lalengke menekankan bahwa prinsip dasar dalam mediasi adalah menjembatani dua kepentingan yang berseberangan agar bertemu di titik tengah. Namun, jika mediasi justru menjadi ajang pemaksaan sepihak tanpa dasar legal yang jelas, maka pengadilan hanya akan mencederai kepercayaan publik terhadap sistem hukum.
“Mau ganti rugi Rp2,5 miliar pun, kalau lahannya tidak jelas, itu sama saja akrobat hukum. Bukan keadilan, tapi jebakan,” tutupnya. (Tim Media/**)
Sumber: Wilson Lalengke
Lulusan pascasarjana bidang Etika Global dan Etika Terapan dari tiga universitas ternama di Eropa.