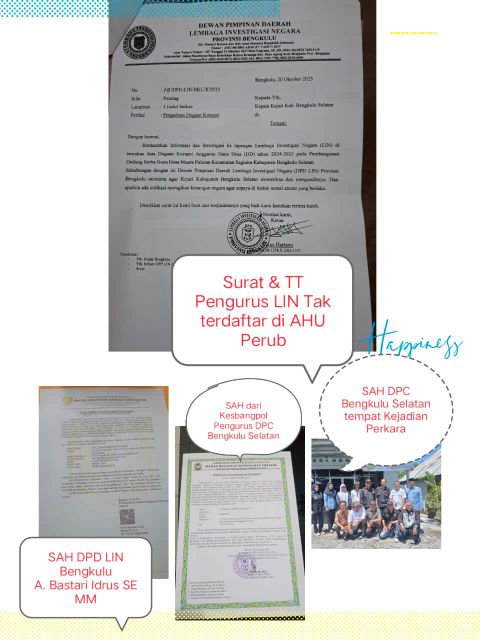Oleh: Edi Darminto
Patrolihukum.net — Indonesia pernah berbangga menjadi salah satu negara demokratis terbesar di dunia, dengan kebebasan pers sebagai salah satu pencapaiannya. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers lahir dari semangat reformasi, menjadi jaminan hukum bagi wartawan untuk menyampaikan informasi secara independen. Namun, dua dekade setelahnya, wajah kebebasan pers justru tampak kusut. “Tinta wartawan bisa berbuah jeruji besi” bukan lagi metafora—ia kini menjadi kenyataan yang menghantui.

Profesi wartawan yang kerap disebut sebagai pilar keempat demokrasi, kini seperti berdiri di bibir jurang. Alih-alih mendapat perlindungan, tak jarang mereka justru menjadi korban tangan-tangan arogan yang bersembunyi di balik lembaga yang mestinya menjadi benteng kebebasan berekspresi. Laporan-laporan yang menjerat wartawan kerap diterima begitu saja oleh aparat, tanpa ruang dialog, tanpa verifikasi mendalam, seolah kata-kata tajam dianggap sama dengan ancaman.
Ironi ini bukan sekadar cerita tunggal. Dalam catatan berbagai organisasi pers, jumlah kasus kekerasan, kriminalisasi, dan intimidasi terhadap jurnalis di Indonesia masih tergolong tinggi. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Dewan Pers pun berulang kali menyerukan pentingnya penegakan Undang-Undang Pers untuk menghindari kriminalisasi karya jurnalistik. Namun, dalam praktiknya, perlindungan hukum itu sering kali tumpul ke atas dan tajam ke bawah.
“Profesi mulia itu kerap dipatahkan,” tulis Sang Pena Sakti dalam artikelnya. Kalimat ini menjadi refleksi dari keresahan banyak jurnalis di lapangan. Ketika keberanian menulis fakta dianggap sebagai upaya “menggiring opini”, kebebasan pers pun seolah hanya slogan. Padahal, jurnalisme tajam adalah nadi yang menjaga demokrasi tetap hidup.
Meski begitu, semangat para kuli tinta belum padam. Di tengah bayang-bayang kriminalisasi, banyak jurnalis tetap memilih menulis fakta, mengungkap kebijakan yang menyimpang, dan menghadirkan suara rakyat ke ruang publik. “Wartawan yang setia pada kebenaran rela lapar, asal suara rakyat tak ikut mati,” menjadi prinsip diam-diam yang mereka pegang.
Pesan yang lahir dari keresahan ini sederhana: pena wartawan adalah tombak kebenaran, bukan senjata kriminal. Tinta bukan ancaman, melainkan cahaya yang menuntun masyarakat memahami realitas. Sejarah pun mencatat, bangsa besar lahir dari keberanian orang-orang yang menulis dan bersuara, bukan dari mereka yang memilih bungkam.
Seruan ini bukan sekadar romantisme profesi. Ia adalah pengingat bahwa demokrasi tidak akan pernah utuh tanpa kebebasan pers yang sehat. Wartawan sejati akan terus menulis kebenaran, meski di bawah tekanan. Tinta takkan pernah mati. Pena takkan pernah tunduk. Dan masyarakatlah yang pada akhirnya akan menjadi saksi, bahwa kebebasan informasi adalah hak yang tak boleh dikorbankan.
(Redaksi MPH)