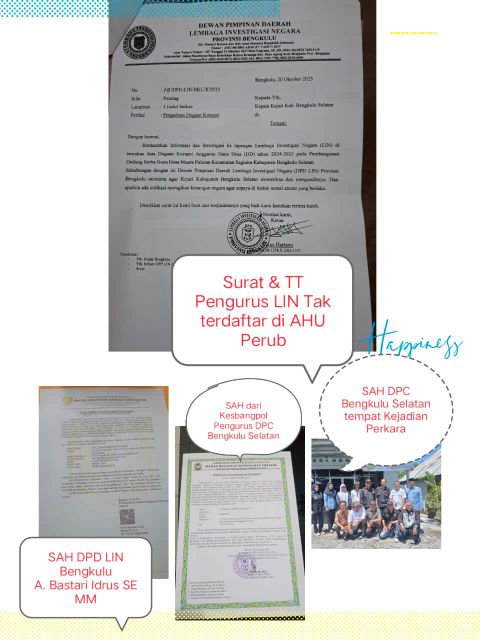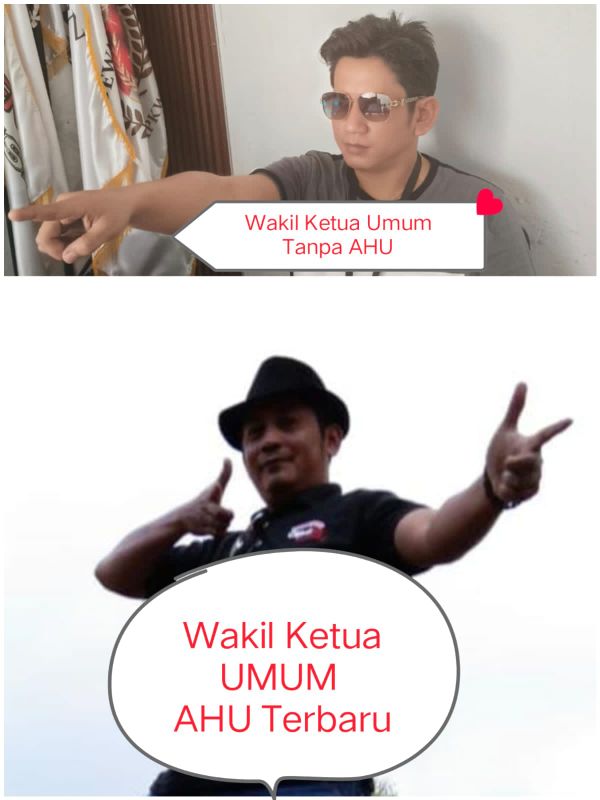Wonogiri — Peristiwa dugaan penipuan politik yang menyeret nama SS, oknum Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Wonogiri, menjadi perhatian publik dalam gelaran Pilkada 2024 yang lalu. Kasus ini melibatkan mantan kader PDI Perjuangan, HT, yang merasa telah ditipu setelah menyerahkan dana politik senilai Rp500 juta dengan harapan mendapatkan rekomendasi pencalonan sebagai bupati dari Partai Gerindra.
Kasus ini tidak hanya menyentuh ranah hukum, tetapi juga membuka wacana penting mengenai etika politik lokal, integritas kader partai, dan kelemahan mekanisme akuntabilitas internal dalam tubuh partai politik di Indonesia.

Awalnya, HT yang saat itu menjabat sebagai anggota Fraksi PDIP di DPRD Wonogiri menyatakan bahwa dirinya ditawari untuk maju sebagai bakal calon bupati melalui jalur Partai Gerindra oleh Ketua DPC Gerindra Wonogiri, SS. Tawaran tersebut disertai janji dukungan penuh dari struktur partai, bahkan disebutkan juga bahwa Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah, SY, hadir dalam beberapa agenda politik bersama.
Atas dasar kesepakatan lisan dan komitmen politik tersebut, HT mengundurkan diri dari PDIP dan menyerahkan dana sebesar Rp500 juta kepada pihak DPC Gerindra. Dana itu, menurut HT, digunakan untuk operasional konsolidasi, logistik kampanye, dan kegiatan-kegiatan penguatan basis massa di tingkat akar rumput.
Namun, secara tiba-tiba, dukungan dari Partai Gerindra dicabut. Belakangan terungkap bahwa pembatalan dukungan tersebut berkaitan dengan adanya manuver politik dari kubu SK—tokoh lain yang juga mencalonkan diri—yang disebut-sebut akan menggandeng menantu SS sebagai calon wakil bupati. Dugaan ini memperkuat spekulasi bahwa pencabutan dukungan bukan karena pertimbangan politik strategis partai, melainkan dilatarbelakangi oleh kepentingan pribadi SS.
Secara sosiologis, kasus ini menggambarkan pola patron-klien dalam politik lokal, di mana elite partai menggunakan kekuasaannya sebagai alat tawar-menawar. Fenomena ini telah lama dikaji dalam teori clientelism oleh ilmuwan politik James C. Scott, yang menyatakan bahwa patronase dalam politik sering kali berujung pada praktik transaksional yang merusak prinsip meritokrasi dan integritas sistem demokrasi.
Relasi semacam ini menyebabkan terjadinya penyalahgunaan wewenang, karena kandidat yang potensial justru tersingkir oleh kandidat yang memiliki kedekatan pribadi dengan pengambil keputusan partai. Politik uang dan lobi-lobi elit menjadi penghalang utama terwujudnya kontestasi Pilkada yang jujur dan terbuka.
Dalam ranah hukum, tindakan SS dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan:
“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”
Lebih jauh lagi, dugaan penipuan dapat ditelusuri melalui Pasal 378 KUHP tentang penipuan yang berbunyi:
“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum… dihukum karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”
Jika benar dana Rp500 juta diserahkan atas dasar janji politik yang kemudian dibatalkan secara sepihak dan tidak seluruhnya dikembalikan, maka unsur pidana dalam kasus ini bisa terpenuhi. Langkah hukum pun bisa ditempuh oleh korban dengan melaporkan kasus ini ke aparat penegak hukum.
Dari sisi etika politik, tindakan seperti ini mencederai kehormatan partai dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi politik. Partai Gerindra sebagai institusi politik seharusnya memiliki mekanisme evaluasi dan pengawasan terhadap kadernya yang menyalahgunakan posisi untuk keuntungan pribadi.
Kasus ini seharusnya dibawa ke Mahkamah Partai atau Dewan Kehormatan partai untuk mendapatkan sanksi internal. Tidak menutup kemungkinan pula, Partai Gerindra Pusat harus turun tangan menyelidiki praktik kotor semacam ini demi menjaga marwah partai di mata publik, meski Pilkada 2024 yang sangat krusial sudah usai.
Kasus HT vs SS menjadi cerminan betapa rapuhnya sistem internal partai politik dalam menjalankan fungsi demokrasi secara sehat. Reformasi struktural dalam rekrutmen calon kepala daerah harus menjadi prioritas utama, dengan menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan meritokrasi.
Bawaslu dan KPK juga perlu ikut mengawasi proses pencalonan kepala daerah yang kerap kali dijadikan ajang transaksi politik, agar Pilkada selanjutnya benar-benar mencerminkan kehendak rakyat, bukan hasil dari lobi-lobi elite dan kepentingan pribadi.
Jika dibiarkan, kasus seperti ini akan memperkuat persepsi publik bahwa partai politik bukanlah sarana perjuangan aspirasi rakyat, melainkan tempat praktik jual beli kekuasaan yang memperkaya segelintir elite. (Tim/Red/**)